Pernahkah Anda membaca artikel di surat kabar, lalu
mengeluhkan gaya bahasa yang cenderung statis, dipakai berulang kali oleh si
penulis? Mungkin, Anda mengeluhkan mengapa prinsip faktual jurnalistik (5W+1H)
hanya dijelajahi secara dangkal? Atau, mungkin juga muncul pertanyaan dalam
benak Anda mengapa saat membaca liputan jurnalistik, Anda tidak bisa
menikmatinya seperti saat membaca novel atau cerpen. Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, Anda mungkin perlu membaca jurnalisme sastrawi.
Apakah jurnalisme sastrawi itu? Jurnalisme sastrawi
adalah suatu aliran jurnalistik yang dipelopori oleh jurnalis-novelis, Tom
Wolfe, dan berkembang pada awal 1970 dengan sebutan jurnalisme baru (new
journalism). Disebut jurnalisme baru, selain karena gaya bahasanya yang berbeda,
aliran ini menggunakan konstruksi situasi demi situasi (scene by scene
construction), reportase yang mendalam (immersion reporting), menggunakan sudut
pandang orang ketiga (third person point-of-view), serta penuh dengan
detail-sangat berbeda dari kebanyakan reportase.
Dalam jurnalisme biasa, 5W+1H merupakan singkatan dari
who (siapa), what (apa), where (di mana), when (kapan), why (mengapa), dan how
(bagaimana). Namun, jurnalisme sastrawi mengubah who menjadi karakter, what
menjadi alur, where menjadi latar, when menjadi kronologi, why menjadi motif,
dan how menjadi narasi. Maka dari itu, reportase-reportase jurnalisme sastrawi
lebih menyerupai novel atau cerpen daripada reportase biasa, tetapi masih tetap
berpegang pada Journalism 101-nya, yaitu penyajian fakta. Akibatnya, reportase
jurnalisme sastrawi selalu membutuhkan banyak halaman, puluhan hingga ratusan.
Bahkan, majalah The New Yorker pernah menerbitkan satu laporan hanya dalam satu
edisi majalah, yaitu “Hiroshima” karya John Hersey yang menceritakan
detik-detik penghancuran Kota Hiroshima oleh tentara Sekutu.
Pada tahun 2000, Andreas Harsono mencoba memperkenalkan
jurnalisme sastrawi di Indonesia. Dia kemudian membentuk tim yang terdiri dari
jurnalis-jurnalis muda berbakat untuk merintis majalah jurnalistik dengan gaya
tulisan dan bahasa yang sastrawi. Lahirlah majalah Pantau pada bulan Desember
2000. Meskipun demikian, setelah berjalan kurang dari 3 tahun, majalah ini
akhirnya berhenti beredar karena kurangnya biaya operasional dan lemahnya
strategi pemasaran. Pada bulan Februari 2003, majalah Pantau resmi dinyatakan
berhenti. Meskipun berhenti, beberapa jurnalis Pantau, termasuk Andreas Harsono,
kemudian mendapatkan ide untuk merangkum artikel-artikel terbaik yang pernah
dimuat di majalah Pantau dalam sebuah buku. Terbitlah kemudian buku Jurnalisme
Sastrawi ini yang merupakan bunga rampai artikel-artikel terbaik dari majalah
pertama (dan satu-satunya) di Indonesia yang menggunakan bahasa sastrawi untuk
tulisan jurnalistik.
Buku ini memuat delapan cerita dari delapan jurnalis
eks-Pantau. Sebagai pembuka, buku ini menawarkan artikel dari Chik Rini, yaitu
“Sebuah Kegilaan di Simpang Kraft” yang menceritakan insiden berdarah yang
terjadi di Prapatan Kraft (Aceh) pada tahun 1999. Dengan sangat dramatis, Chik
Rini menceritakan kejadian tersebut dan menggunakan reporter RCTI, Imam
Wahyudi, dan juru kameranya, Fipin Kurniawan, sebagai tokoh utama. Anda mungkin
tidak akan menemukan artikel di surat kabar atau majalah manapun tentang detail
tertembaknya seorang bocah tepat di kepala sampai cairan otaknya terburai dan
membuat sebagian wartawan yang meliput gemetaran, menangis, dan muntah, kecuali
dalam tulisan Chik Rini yang reportasenya begitu mendalam ini.
Kemudian, ada
Agus Sopian yang menceritakan secara cermat bagaimana kinerja teroris pelaku
sejumlah teror bom di Indonesia melalui artikel yang berjudul “Taufik bin Abdul
Alim”. Disusul kemudian oleh “Hikayat Kebo”, sebuah reportase oleh Linda
Christanty yang menyikapi pembakaran hidup-hidup seorang gelandangan bernama
Kebo di Jakarta. Ada pula “Konflik Nan Tak Kunjung Padam” karya Coen Husain
Pontoh yang menyingkap semua kebobrokan majalah tersohor di Indonesia, Tempo.
“Kejar Daku Kau Kusekolahkan” oleh Alfian Hamzah menceritakan suka-duka TNI
yang ditempatkan di Aceh pada masa DOM. Kata kata yang digunakan oleh
tentara-tentara Batalyon Rajawali yang bertugas di Aceh ternyata mempunyai
makna khusus, misalnya, kata sekolah berarti ‘membunuh awak GAM dengan tembakan
langsung di kepala’.
Lalu, ada artikel milik Eriyanto yang berjudul “Koran,
Bisnis, dan Perang” yang bertutur mengenai dua koran besar di Maluku, Suara
Maluku dan Ambon Ekspres, yang mempunyai andil dalam memperkeruh konflik agama
yang sedang terjadi. Selanjutnya, Budi Setiyono dalam “Ngak-Ngik-Ngok”
bercerita tentang Koes Plus yang ditunjuk Presiden Soekarno untuk menjadi “duta
Nekolim” setelah mereka dipenjara. Yang terakhir adalah tulisan Andreas Harsono
sendiri yang berjudul “Dari Thames ke Ciliwung” yang menggambarkan bobroknya
birokrasi PDAM Jaya beserta investor-investornya dalam hal pengelolaan air di
Jakarta.
Thanks to http://lidahibu.com/
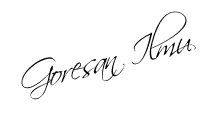













0 komentar:
Posting Komentar